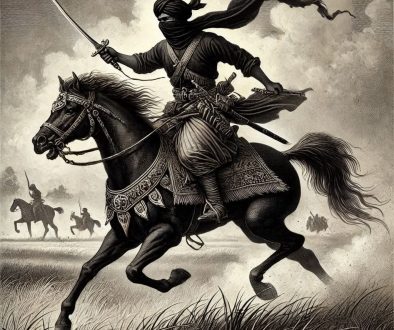Jatigede: Kisah Kota yang Tenggelam dalam Arus Peradaban
SUMEDANG – Di antara kabut pagi yang menggantung rendah di langit Sumedang, terdapat sebuah kisah yang nyaris dilupakan waktu.
Dahulu, lembah yang kini menyatu dengan birunya permukaan air Waduk Jatigede adalah hamparan sawah subur dan perkampungan yang menyimpan jejak sejarah.
Namun, takdir berkata lain. Ombak peradaban telah menenggelamkan kisah itu ke dalam pusaran air yang tak bertepi.

Waduk Jatigede, yang digagas sejak era Orde Lama dan akhirnya diwujudkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, menjadi monumen bisu dari pengorbanan ratusan desa.
Ratusan rumah yang pernah menjadi saksi kehidupan kini telah menjadi istana ikan. Jalan-jalan setapak yang dulu dilewati para petani, kini hanya bisa ditemui dalam ingatan mereka yang tersisa.

Seperti Atlantis di Nusantara, perkampungan yang pernah hidup kini menjadi kota bawah air. Tak hanya sawah dan rumah yang hilang, tetapi juga jejak budaya yang tak ternilai harganya.
Situs-situs bersejarah, makam leluhur, dan tempat-tempat suci yang selama ratusan tahun menjadi bagian dari identitas warga, kini terkubur dalam kedalaman yang sunyi. Hanya suara gemuruh angin yang membawa bisikan masa lalu di antara riak air yang tenang.

Bagi mereka yang dahulu menghuni tanah ini, Jatigede bukan sekadar proyek bendungan, melainkan pemisah antara kenangan dan kenyataan.
Mereka yang terpaksa meninggalkan rumahnya kini harus mengukir lembaran baru di tempat yang asing, sementara kampung halaman mereka tinggal menjadi dongeng bagi generasi berikutnya.
Di permukaan, Waduk Jatigede menjanjikan manfaat bagi banyak orang—air untuk irigasi, pembangkit listrik, serta pencegahan banjir.

Namun, di kedalamannya, ada tangisan yang tak terdengar, ada doa yang tak tersampaikan.
Seperti kisah-kisah tua yang tenggelam dalam lautan sejarah, Jatigede kini menjadi legenda baru yang diceritakan dengan rindu.

Di balik semua itu, air yang menelan Jatigede kini menjadi cermin bagi negeri ini: bahwa pembangunan sering kali menuntut pengorbanan, bahwa kenangan bisa luruh dalam arus perubahan, dan bahwa setiap kemajuan memiliki harga yang harus dibayar—bahkan jika yang harus dikorbankan adalah sejarah itu sendiri. (ALN)