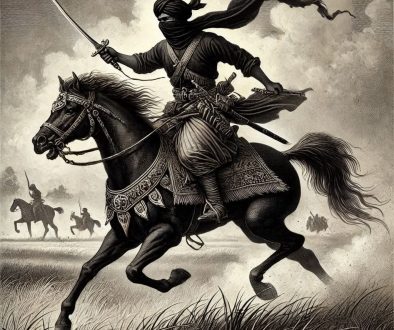Mata Air Sejarah Cipancar yang Tak Pernah Kering: Haul Leluhur sebagai Pengingat Jati Diri
Portal Kawasan, SUMEDANG – Cipancar, tanah yang telah menyimpan jejak para leluhur selama berabad-abad, kembali berbisik kepada generasi penerusnya. Pohon-pohon tua di Astana Gede Cipancar seolah merunduk khidmat menyaksikan Haul Leluhur Cipancar Sumedang yang digelar dengan penuh penghormatan pada 9 Februari 2015 lalu.
Mereka seakan ingin menyampaikan bahwa akar sejarah tak boleh tercerabut, bahwa cahaya obor masa lalu harus terus menyala agar tak tenggelam dalam kegelapan zaman.
Pondok Pesantren Seni Budaya Pancer Jati, yang saya dirikan, menjadi saksi bisu bagaimana acara ini bukan sekadar seremonial, tetapi sebuah perjalanan spiritual untuk meneguhkan kembali jati diri.

Bersanding dengan ritual Manaqib Syekh Abdul Qâdir al-Jailânî yang rutin diadakan setiap bulan, haul ini menjadi momen refleksi—sebuah percakapan antara masa kini dan masa lalu, di mana generasi terdahulu hadir dalam bentuk nilai, semangat, dan hikmah yang tak lekang oleh waktu.
Dari bibir Pak Toto Satori, sang juru kunci, mengalir kisah-kisah yang selama ini tersembunyi dalam tanah Cipancar. Teks-teks kuno pun seolah berbisik lebih lantang di benak saya, menuntun pada pemahaman baru tentang jejak leluhur yang telah tertanam begitu dalam. Cipancar bukan sekadar desa, melainkan sebuah kitab terbuka yang menunggu untuk dibaca ulang, dikaji, dan dipahami dengan hati yang bening.
Sejarah Cipancar seperti sungai yang mengalir jauh, bermuara pada peristiwa besar dalam lembaran “Carita Parahyangan”. Dalam riak-riaknya, mengapung kisah Prabu Purbasora, raja keempat dari Galuh, yang melarikan diri bersama Ratu Komalasari dan Aria Bimaraksa.
Langkah mereka terhenti di tempat di mana mata air memancar dari bumi, membuat Prabu Purbasora terperanjat dan mengucapkan kata yang kelak menjadi nama abadi: Cipancar. Mata air itu tetap ada hingga kini, mengalir sebagai saksi bisu perjalanan takdir.
Lalu, hadir pula sosok Sunan Pancer, atau Sunan Baeti, yang namanya terselubung dalam kabut waktu. Seperti daun kering yang diterbangkan angin, kisahnya tersebar dalam berbagai versi, tetapi tetap menuju satu akar yang sama—ia adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Sunda.
Bersama pasangannya, Aria Bimaraksa, mereka dikenang dalam tradisi lisan sebagai “Aki Balangantrang” dan “Nini Balangantrang”, sosok yang keberadaannya masih terasa dalam ingatan kolektif masyarakat Cipancar.

Namun, sejarah bukan hanya tentang menengok ke belakang. Ia adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Seperti yang ditegaskan dalam penelitian Prof. Dr. Ajid Thohir dan didukung oleh riset Prof. Dr. Agus Aris Munandar serta Irjen Pol. Drs. Anton Charliyan, kehadiran Islam di Cipancar mungkin lebih awal dari yang selama ini diperkirakan.
Jika benar Sunan Pancer dan Aria Bimaraksa telah memeluk Islam pada abad ke-7 atau ke-8 M, maka jejak keislaman di Tatar Pasundan bukanlah sekadar riak kecil, melainkan gelombang yang telah lama mengayun peradaban.
Dari rahim sejarah ini pula lahir Prabu Guru Aji Putih, yang kemudian menjadi pendiri Kerajaan Tembong Agung, cikal bakal Sumedang Larang. Cipancar, yang dulu hanya dianggap sebagai titik kecil di peta, ternyata memiliki peran besar dalam mengalirkan narasi besar Nusantara.
Namun, Haul Leluhur Cipancar bukan tentang kebanggaan akan silsilah semata. Ia adalah pengingat bahwa sejarah bukan untuk disimpan dalam lemari berdebu, melainkan untuk dijadikan cermin dalam membangun masa depan. Generasi yang paham akar sejarahnya akan tumbuh kuat seperti pohon yang berdaun rimbun, memberikan keteduhan bagi yang datang setelahnya.
Cipancar telah berbicara melalui mata airnya, melalui desir anginnya, dan melalui suara-suara leluhur yang mengalir dalam darah kita. Kini, giliran kita untuk mendengarkan, memahami, dan melanjutkan perjalanan ini dengan nyala obor yang tak pernah padam.
Sumber: Dodo Widarda, Pimpinan Pondok Pesantren Seni Budaya Pancer Jati Sumedang, (Edit : ANG/ALN)